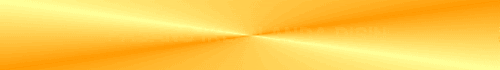![[Image: pinisi.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoSi1Uy1tUovO01D8hZIeIgrqAsl125hSXYH5iUGYeb1fsgazRVAYZ5-nPYUmCECOdn0pMO8fBnxC6cafH24yUJQoOt9Bh6vUrv-wmdaSXrD1X0P0mv3k4ALsZRW5c4WTXl7XuGjrHukw/s1600/pinisi.jpg)
Tanah beru, tanah leluhur para arsitek perahu Pinisi. Di tanah inilah Panrita Lopi melahirkan karya besar mereka. Menciptakan perahu yang hingga saat ini masih melayari pesisir pantai nusantara. Dimuali dari awal sejarah Bugis klasik hingga zaman cybernetic perahu Pinisi tetap anggun meniti arus, membelah ombak menggapai pantai tujuan. Masih segar dalam ingatan ketika pinisi Amanagappa dengan gagah berlayar ke semenanjung Madagaskar. Juga Hati Herage dan Damarsagara yang berlayar ke Australia dan Jepang. Seolah ingin memperlihatkan pada dunia bahwa inilah anak bangsa yang telah menoreh kisah dalam lontara zaman berzaman. Sejenak, ingin rasanya berada di Bonto Bahari dan menyaksikan kepiawaian pencipta perahu-perahu handal yang dengan mahir melahirkan karya besar mereka. Sungguh, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap jengkal badan perahu sarat dengan nilai falsafah.
Perahu pinisi dari zaman dahulu hingga saat ini telah menorehkan kisah panjang. Pinisi telah menjelma menjadi armada perang, kapal angkut barang dagangan hingga kapal pesiar yang dilengkapi peralatan mewah sekelas hotel berbintang. Seperti apakah sesungguhnya perahu ini dilahirkan, berikut sekelumit gambaran tentang proses pebuatan perahu pinisi yang terkenal handal dalam arung samudra.
a. Proses pencarian bahan dasar
![[Image: 1905403p.JPG]](http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2009/11/16/1905403p.JPG)
Proses pencarian kayu yang menjadi bahan dasar pembuatan kapal pinisi diawali dengan penentuan hari baik yang dipandang menguntungkan. Lazimnya, hari ini dipilih pada hari ke lima dan ketujuh bulan berjalan. Penentuan hari ini didasari oleh nilai filosofi yakni jika hari kelima maka itu berarti Naparilimai dale’na. Lima dalam bahasa bugis berarti angka lima yang juga berarti telapak tangan. Naparilimai dale’na dapat dimaknakan dale’ atau rezeki diharapkan nantinya akan berada ditelapak tangan. Atau dengan makna lain rezeki mudah dicari jika kelak perahu yang akan dibuat dimanfaatkan untuk mencari rezeki atau keuntungan. JIka dipilih hari ketujuh, maka itu berarti Natujuangenggi dalle’na. Natujuang dalam bahasa Bugis berarti diniatkan atau dapat pula berarti didapatkan. Natujuangenggi dalle’na memberi makna kemudahan dalam memperoleh dalle’ (rezeki) atau apa saja yang menjadi niat dihati maka apa yang diniatkan itu mudah didapatkan.
![[Image: Pembuatan+Kapal+.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_QxYL1v2mZkdotM0SYOY2pUqJWsGtFNctw_m-RUFSwJEQ0zuobd6LJjTERAhYTl5pClD-zFn-SavrliHsUwC-TZR4c54JUKcq81Tzp6VfsyDzIClnxDH9M9GZlJrRsL8OIw9pUwl0_uXW/s320/Pembuatan+Kapal+.jpg)
Pemilihan kayu juga tidak dapat dilakukan secara serampangan, tapi dengan melalui proses pemilihan dengan penyelenggaraan ritual tertentu. Biasanya diawali dengan pemotongan ayam dan permintaan izin agar penghuni pohon atau makhluk halus yang diyakini mendiami pohon tersebut memberikan izin agar kayu tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembuatan perahu. Proses pemotongan ini juga harus dilaksanakan sekaligus, tidak boleh berhenti dikerjakan sebelum pohonnya tumbang. Karenanya, proses pemotongan yang lazimnya menggunakan gergaji dilakukan oleh laki-laki yang berbadan kuat.
Spoiler (Click to Hide)
![[Image: Phinisi+tanahberu.JPG]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjig9kDUSOJEPiBPpnZfq599BPsEYbDjpJk1dXPDPPMDjHeSHB9Za7ZIVDOdLTUbNctBhkUUirhNd7ix2M0H1A6WwBHBW4Iik4nfc3WQ_B20cxyXLnJ9af_b9__uybbhknWJfBoLDWjL7eZ/s1600/Phinisi+tanahberu.JPG)
Pemotongan kayu untuk dijadikan lunas juga memiliki aturan tersendiri. Kayu bagian ujung yang dipotong dan tidak dapat dimanfaatkanakan dibuang kelaut. Proses pengantaran bagian ujung ini juga tidak boleh menyentuh tanah hingga kemudian dibuang kelaut. Upacara pengantaran ini lazim disebut ritual annattara. Bagian yang dibuang ini melambangkan laki-laki yang melaut untuk mencari nafkah atau juga dapat diartikan sebagai penolak bala. Selanjutnya potongan bagian belakang akan disimpan dirumah, sebagai symbol seorang istri yang menanti kedatangan suami yang sedang mencari nafkah dengan melaut.
Spoiler (Click to Hide)
![[Image: perahu+phinisi+--+foto+Vierta+Dewi+Aulia.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiApopntOd64T3KTzCOo0tNRc8icXbIfMtzV_uSXyZyDul68MAR5-rAp-z_jk7fSbVb1rvxS-sBbxwgJm7Nl3EMpR78yulHnljZ5l2pUGX46yrqVlRdVC9cw_DomIzCgMY_JeX6vMBS7MW-/s1600/perahu+phinisi+--+foto+Vierta+Dewi+Aulia.jpg)
Penentuan bagian yang menjadi pusat perahu atau ini lebih menitik beratkan pada nilai filosofis yang terkandung didalamnya, yakni melambangkan kelahiran bayi perahu. Selanjutnya proses pengerjaan perahu dilaksanakan dengan dikomandani oleh seorang Ponggawa. Ponggawa ini pulalah yang bertanggungjawab terhadap proses pembuatan perahu secara teknis hingga selesai.
![[Image: 182998_173348579377473_100001069979167_4...7454_n.jpg]](http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/182998_173348579377473_100001069979167_405839_87454_n.jpg)
Proses selanjutnya adalah menyiapkan teras dan buritan perahu yang menjadi badan perahu. Proses ini diawali dengan pemasangan lunas perahu yang kemudian dusul dengan pemasangan linggi depan dan linggi belakang. Barulah kemudian jika selesai disusul pemasangan papan yang menjadi diding lambung perahu. Secara berurut juga dipasang tulang dan gading perahu. Setelah proses pemasangan gading ini selesai perahu dipasangi balok-balok dinding dan dek. Jika semuanya rampung menyusul kamar perahu yang akan dikerjakan. Namun, perlu dijadikan catatan dalam proses pembuatan dan pemasangan beberapa bagian perahu, juga dikerjakan perekatan antara bagian yang menjadi komponen perahu. Perekatan ini dilakukan dengan memanfaatkan kulit pohon Barru dan dempul yang terbuat dari kapur dan minyak kelapa.
Seperti diketahui bahwa proses pembuatan kapal dikomandani oleh seorang punggawa atau orang yang mengerti tentang pembuatan perahu secara tekhnis. Punggawa ini kemudian memiliki tanggung jawab terhadap pembagian kerja yang dilaksanakan oleh para pembatu atau pekerja yang disebut Sawi. Disamping itu seorang punggawa juga ditutut mampu memberikan pengarahan dan pengetahuan kepada para sawi sebagai pelaksana teknis. Sawi sendiri secara khusus sulit diketahui kemampuannya selain keterlibatannya sebagai pekerja dalam proses pembuatan perahu hingga selesai.
“Bismillahir Rahmanir Rahim BuIu-bulunnako buttaya, patimbonako bosiya,
kayunnako mukmamulhakim, laku sareang Nabi Haidir” Demikian kalimat yang
berisi doa dan harapan terhadap awal pelayaran mengawali perahu pinisi
diluncurkan. Proses penurunan perahu ke laut disamping diiringi doa juga
diselenggarakan helatan berupa penyembelihan hewan (sapi) sebagai rasa
syukur atas terlaksananya pembuatan perahu tersebut.
![[Image: 20100918_112022_a%20copy.jpg]](http://www.bugisonline.com/images/stories/20100918_112022_a%20copy.jpg)
Dari proses pembuatan ini tergambar beberapa bagian perahu pinisi yang
memiliki fungsi dalam menggerakkan kapal. Bagian-bagian tersebut antara
lain :
1. Anjong, (segi tiga penyeimbang) berada pada bagian depan kapal.
2. Sombala (layar utama) berukuran besar
3. Tanpasere (layar kecil) berbentuk segitiga ada di setiap tiang utama.
4. Cocoro pantara (layar bantu depan).
5. Cocoro tangnga (layar bantu tengah.
6. Tarengke (layar bantu di belakang)
Kilas sejarah perahu pinisi
Berawal dari mitologi dan kepercayaan masyarakat terhadap sosok Sawerigading yang berlayar dari tanah luwu untuk mempersunting seorang putri bernama We Codai. Keberangkatan Sawerigading ini berlayar menggunakan sebuah kapal yang terbuat dari sebuah pohon bernama Welenreng. Pohon ini ditempah untuk dijadikan perahu yang akan digunakan oleh Sawerigading dalan pelayarannya. Namun, perahu ini diterpa badai dan akhirnya pecah. Bagian perahu yang telah hancur ini kemudian terdapar di tiga tempat, bagian haluan dan buritan terdampar di Lemo-lemo. Bagian lambung kapal terdampar di sebuah desa bernama Ara dan layarnya terdampar di Bira. Oleh masyarakat ketiga daerah ini mengumpulkan puing puing perahu Sawerigading dan mereka ulang bentuknya.
Dari sinilah awal munculnya mitologi bahwa ketiga daerah tersebut memiliki keahlian spesifik berdasarkan temuan puing-puing kapal tersebut. Orang Bira yang diyakini mendapatkan layar kelak memiliki keterampilan berlayar dan navigasi. Orang Ara memiliki kemampuan spesifik dalam pembuatan lambung kapal dan sebaliknya orang Lemo-lemo lebih mahir membuat haluan dan buritan perahu. Ketiga daerah ini berada di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan,yang kemudian tersohor sebagai pembuat perahu pinisi.
Pada awal abad ke-18 para pelaut Bira menakhodai pinisi padewakang hingga ke pantai utara Australia demi memburu teripang kualitas terbaik. Padewakang yang mampu membawa muatan hingga 140 ton berkeliling menghimpun barang dari berbagai pelosok Nusantara; rotan, lilin, agar-agar, sirip hiu, kulit, daging kering, kulit penyu, sarang burung, dan tikar rotan; dan menjualnya kepada saudagar kapal jung dari China. Guncangan politik lokal tahun 1950-an, kelangkaan kayu, dan perkembangan teknologi kapal motor membuat kejayaan Semenanjung Bira memudar. Namun, punggawa Semenanjung Bira menolak menyerah.
Thomas Gibson dalam bukunya, Kekuasaan Raja, Syaikh, dan Ambtenaar-Pengetahuan Simbolik & Kekuasaan Tradisional Makassar 1300–2000 (Penerbit Ininnawa, 2009), mengurai diaspora tukang kapal Desa Ara dan Lemo-lemo yang meninggalkan Semenanjung Bira demi melanjutkan jalan hidup mereka sebagai punggawa pinisi.
Menurut Gibson, punggawa Desa Lemo-lemo sejak awal abad ke-19 mulai meninggalkan Semenanjung Bira, punggawa pinisi di mana-mana. ”(Sementara) para pembuat perahu Desa Ara (hingga awal 1950-an tetap) bergantung kepada saudagar kaya di Bira … (Namun) pemberontakan Darul Islam (membuat) pangkalan perahu di Bira dan Bone ditutup … Para punggawa (Desa Ara) mulai (pergi dan) membuka kontak dengan saudagar Tionghoa di seluruh Indonesia. Mereka kembali ke Ara, merekrut awak pembuat kapal (yang lantas dibawa ke) tempat para pemesan. Di Pulau Laut, Kalimantan Selatan, dibangun perahu yang bobotnya hingga 600 ton,” tulis Gibson.
Gibson mencatat, pada 1988 koloni orang Ara tersebar di Indonesia. Mulai dari Jampea, Selayar, Sulawesi Selatan; Merauke dan Sorong di Papua; Kupang di Nusa Tenggara Timur; Ambon dan Ternate di Kepulauan Maluku; Tarakan, Balikpapan, Batu Licin, Kota Baru, Banjarmasin, Sampit, Kuala Pembuangan, Kumai, dan Pontianak di Kalimantan; Jakarta; Surabaya; hingga Belitung, Palembang, dan Jambi di Sumatera.
1. Anjong, (segi tiga penyeimbang) berada pada bagian depan kapal.
2. Sombala (layar utama) berukuran besar
3. Tanpasere (layar kecil) berbentuk segitiga ada di setiap tiang utama.
4. Cocoro pantara (layar bantu depan).
5. Cocoro tangnga (layar bantu tengah.
6. Tarengke (layar bantu di belakang)
Kilas sejarah perahu pinisi
Berawal dari mitologi dan kepercayaan masyarakat terhadap sosok Sawerigading yang berlayar dari tanah luwu untuk mempersunting seorang putri bernama We Codai. Keberangkatan Sawerigading ini berlayar menggunakan sebuah kapal yang terbuat dari sebuah pohon bernama Welenreng. Pohon ini ditempah untuk dijadikan perahu yang akan digunakan oleh Sawerigading dalan pelayarannya. Namun, perahu ini diterpa badai dan akhirnya pecah. Bagian perahu yang telah hancur ini kemudian terdapar di tiga tempat, bagian haluan dan buritan terdampar di Lemo-lemo. Bagian lambung kapal terdampar di sebuah desa bernama Ara dan layarnya terdampar di Bira. Oleh masyarakat ketiga daerah ini mengumpulkan puing puing perahu Sawerigading dan mereka ulang bentuknya.
Dari sinilah awal munculnya mitologi bahwa ketiga daerah tersebut memiliki keahlian spesifik berdasarkan temuan puing-puing kapal tersebut. Orang Bira yang diyakini mendapatkan layar kelak memiliki keterampilan berlayar dan navigasi. Orang Ara memiliki kemampuan spesifik dalam pembuatan lambung kapal dan sebaliknya orang Lemo-lemo lebih mahir membuat haluan dan buritan perahu. Ketiga daerah ini berada di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan,yang kemudian tersohor sebagai pembuat perahu pinisi.
Pada awal abad ke-18 para pelaut Bira menakhodai pinisi padewakang hingga ke pantai utara Australia demi memburu teripang kualitas terbaik. Padewakang yang mampu membawa muatan hingga 140 ton berkeliling menghimpun barang dari berbagai pelosok Nusantara; rotan, lilin, agar-agar, sirip hiu, kulit, daging kering, kulit penyu, sarang burung, dan tikar rotan; dan menjualnya kepada saudagar kapal jung dari China. Guncangan politik lokal tahun 1950-an, kelangkaan kayu, dan perkembangan teknologi kapal motor membuat kejayaan Semenanjung Bira memudar. Namun, punggawa Semenanjung Bira menolak menyerah.
Thomas Gibson dalam bukunya, Kekuasaan Raja, Syaikh, dan Ambtenaar-Pengetahuan Simbolik & Kekuasaan Tradisional Makassar 1300–2000 (Penerbit Ininnawa, 2009), mengurai diaspora tukang kapal Desa Ara dan Lemo-lemo yang meninggalkan Semenanjung Bira demi melanjutkan jalan hidup mereka sebagai punggawa pinisi.
Menurut Gibson, punggawa Desa Lemo-lemo sejak awal abad ke-19 mulai meninggalkan Semenanjung Bira, punggawa pinisi di mana-mana. ”(Sementara) para pembuat perahu Desa Ara (hingga awal 1950-an tetap) bergantung kepada saudagar kaya di Bira … (Namun) pemberontakan Darul Islam (membuat) pangkalan perahu di Bira dan Bone ditutup … Para punggawa (Desa Ara) mulai (pergi dan) membuka kontak dengan saudagar Tionghoa di seluruh Indonesia. Mereka kembali ke Ara, merekrut awak pembuat kapal (yang lantas dibawa ke) tempat para pemesan. Di Pulau Laut, Kalimantan Selatan, dibangun perahu yang bobotnya hingga 600 ton,” tulis Gibson.
Gibson mencatat, pada 1988 koloni orang Ara tersebar di Indonesia. Mulai dari Jampea, Selayar, Sulawesi Selatan; Merauke dan Sorong di Papua; Kupang di Nusa Tenggara Timur; Ambon dan Ternate di Kepulauan Maluku; Tarakan, Balikpapan, Batu Licin, Kota Baru, Banjarmasin, Sampit, Kuala Pembuangan, Kumai, dan Pontianak di Kalimantan; Jakarta; Surabaya; hingga Belitung, Palembang, dan Jambi di Sumatera.
![[Image: f_2098757638fm_9e208ba.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcAsIQTt7chKeeq6RA7_615FctZ2RrRXRyToqRohJzEvtClgaLZOZ-PO8C2CXAoHDsqQIUDBWzEuAEiUa96tUJm-lHVBe61yWyUSNqgltVtklJPauAsFezjcsenfb34PnpOXsdkzbpHNtr/s1600/f_2098757638fm_9e208ba.jpg)
Sumber