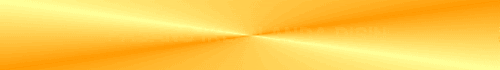Korupsi dan suap menjadi lahan para pejabat negara, karena merekalah yang punya wewenang mengatur harta negara; merekalah yang punya otoritas untuk bertindak atas nama negara. Jangan salahkan rakyat atau pengusaha ikutan menyuap, sebab mereka melakukan itu karena terpaksa.
Jadi, sumber malapetaka negeri ini adalah para pejabat negara yang gemar melakukan korupsi dan menerima suap. Para pejabat negara itu adalah mereka yang duduk di legislatif, eksekutif maupun yudikatif.
Di lingkungan eksekutif, korupsi paling sering terjadi karena kendali harta negara dan pelaksanaan kebijakan ada di sini. Tidak hanya pejabat politik, yakni mereka yang terpilih secara periodik, presiden, menteri dan kepala daerah, tetapi juga pejabat birokrasi yang menguasai administrasi.
Pascatumbangnya Orde Baru, lokasi korupsi merambah ke legislatif. Sebab, kewenangan lembaga ini diperluas. Undang-undang takkan jadi kalau DPR tak membahasnya; demikian juga anggaran nasional takkan sah bisa DPR menolaknya. Padahal dalam soal perencanaan anggaran, kini DPR sampai bicara tingkat teknis: berapa nilai proyek, lalu siapa pelaksananya.
Bagaimana dengan yudikatif? Sejak dulu, lembaga peradilan sudah dikenal paling buruk reputasinya. Putusan hakim bisa diperjualbelikan. Kalau putusan hakim seperti itu, tentu saja juga menular ke jaksa yang bertindak sebagai penuntut dan polisi yang membuat berkas perkara. Mafia hukum menjerat mereka yang ingin menggapai keadilan.
Pada zaman Orde Baru dulu, banyak orang beranggapan korupsi merajalela karena para pejabat yang duduk di legislatif maupun eksekutif tidak akuntabel. Mereka tidak mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat, sebab mereka lebih takut pada atasannya.
Para anggota DPR maupun menteri, diangkat dan diberhentikan oleh presiden; demikian juga para anggota DPRD dan kepala daerah. Kekuasaan tersentralisasi di Istana Negara dan birokrasi sekretariat negara, sekretariat negara menjadi suprabirokrasi. Situasi ini akan berbalik, bila para pejabat publik tadi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.
Tetapi oh tetapi, setelah pemilu demokratis digelar tiga kali, korupsi semkin menjadi-jadi. Politik transaksional merajalela di lingkungan legislatif dan eksekutif. Rakyat dipersalahkan karena mereka selalu minta uang untuk memberikan suaranya. Padahal rakyat punya 'rasionaltias' sendiri: ngapain harus calon yang tidak jelas komitmen dan kemampuannya?
Jual beli suara yang awalnya dimulai para calon, apakah calon anggota legisaltif atau calon pejabat eksekutif, menjadi bumerang. Mereka terjerat utang. Yang gagal terpilih jatuh miskin, yang terpilih berkeras membayar utang dan menyiapkan pundi-pundi untuk pemilu berikutnya. Dari mana meraka akan dapat uang banyak kalau tidak memanfaatkan pengelolaan dana negara.
Sungguh ironis, pemilu kada pertama kali di republik ini terjadi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang digelar 1 Juni 2005. Hasilnya kita sudah sama tahu, kepala daerah terpilihnya dijebloskan penjara oleh KPK. Setelah itu sejumlah kepala daerah menjadi tersangka dan terpidana.
Hingga Desember 2010 terdapat 17 gubernur yang jadi tersangka kasus korupsi. Sementara, dari 497 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 138 bupati/walikota yang tersjerat kasus korupsi. Jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat hasil audit BPK menunjukkan banyaknya pemerintah daerah yang tidak benar dalam mengelola dana negera.
Sementara jumlah anggota DPRD yang masuk penjara sudah tidak terhitung. Itu terjadi dalam situasi di mana jual beli perkara mudah dilakukan. Sudah terbukti, aparat kejaksaan dengan gampang mengubah status tersangka menjadi bebas, demikian juga para hakim.
Coba kalau semua kasus itu ditangani KPK dan diproses di pengadilan khusus tipikor. Bisa dibayangkan betapa sesaknya sel tahanan atau penjara. Ini dengan asumsi para petugas sel tidak gampang disogok. Kalau tidak, ya hukum takkan pernah bikin takut orang masuk penjara.
Bagaimana dengan tingkat nasional. Kondisinya lebih buruk. Hanya karena para pemainnya sudah semakin pintar, maka praktik korupsi dan suap menyuap, tidak bisa ditindak oleh aparat penegak hukum. Apa yang menimpa Partai Demokrat dengan Nazaruddinnya menunjukkan hal itu.
Masih banyak Nazarddin-Nazarddin yang lain, dan tentu saja Partai Demokrat bukan satu-satunya partai yang melindungi anggotanya yang korup. Sebab, partai juga menggantungkan dana dari mereka. Sebab di sini, partai bukanlah alat perjuangan sebagaimana digembar-gemborkan pendiri dan pengurusnya; partai adalah alat mencari kekuasaan, memupuk kekayaan.
*) Didik Supriyanto adalah wartawan detikcom. Tulisan ini tidak mencerminkan kebijakan redaksi.
Sumber: DETIK.COM